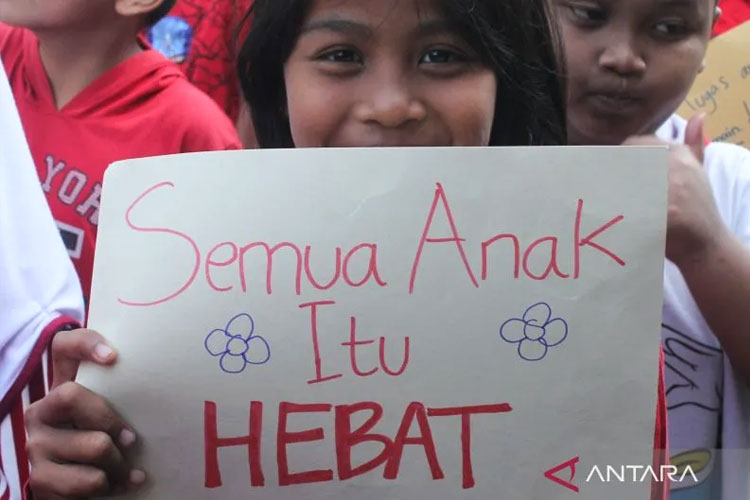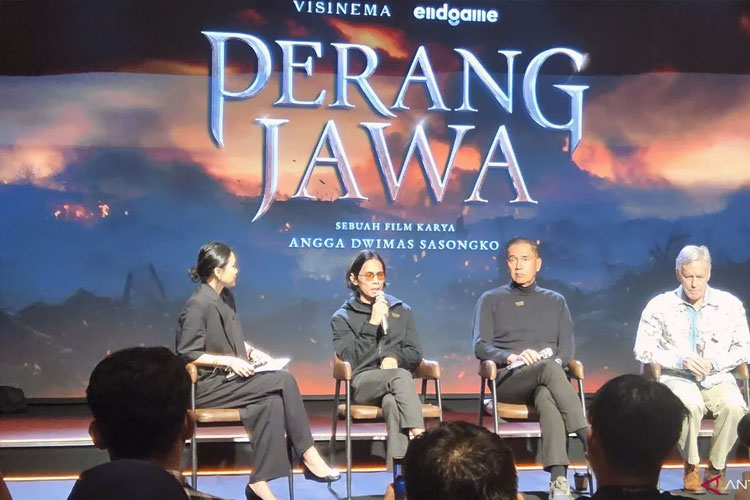TIMES TANGERANG, TANGERANG – Publik geger saat Bank Dunia melansir data mengejutkan: 68,3% warga Indonesia (194,72 juta jiwa) dikategorikan miskin per 2024. Bandingkan dengan BPS yang mencatat hanya 8,47% (23,85 juta jiwa) pada Maret 2025. Bukan soal data siapa yang benar, tapi metodologinya memang beda jalur.
Bank Dunia baru saja merombak standar garis kemiskinan global lewat PPP 2021. Hasilnya? Garis kemiskinan Indonesia melompat dari US$6,85 ke US$8,30 PPP per hari. Dampaknya, yang tadinya “tidak miskin” langsung tercatat miskin dalam hitungan Bank Dunia.
Sementara BPS tetap dengan metode kebutuhan dasar (CBN) yang lebih membumi: pengeluaran minimal untuk hidup layak di Indonesia, termasuk makan 2.100 kalori, sekolah, transportasi, hingga kesehatan.
Garis kemiskinan nasional BPS pada Maret 2025 hanya Rp609.160 per bulan per orang, jauh dari standar Bank Dunia yang mencapai Rp1,5 juta.
Di sinilah letak jurangnya: kemiskinan “global” versi Bank Dunia dan kemiskinan “pemerintah” ala BPS. Tidak soal datanya salah atau benar, melainkan sudut pandang yang bertolak belakang.
Bank Dunia pakai Purchasing Power Parity (PPP) agar bisa membandingkan daya beli antarnegara secara setara. Lantaran Indonesia sudah naik kelas menjadi negara berpendapatan menengah atas (Upper Middle Income Country/UMIC), garis kemiskinannya ikut naik.
Konsekuensinya, angka kemiskinan otomatis melonjak. Di sisi lain, BPS tetap memotret kemiskinan dengan kacamata lokal: seberapa besar biaya hidup minimum di Indonesia.
Bagi kebijakan domestik, data BPS lebih relevan. Program bansos seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang mengikuti garis kemiskinan BPS.
Bahkan Bank Dunia pun mengakui, data BPS adalah rujukan pokok bagi program-program di dalam negeri. Walau, data Bank Dunia tetap dibutuhkan untuk keperluan perbandingan global. Problemnya, angka-angka ini sering bikin gaduh pasalnya dipahami secara mentah, tanpa konteks.
Persoalan ini membawa kita pada dilema yang besar: Indonesia di persimpangan antara ekonomi kerakyatan dan kapitalisme. Di atas kertas, kita menganut ekonomi Pancasila ala Pasal 33 UUD 1945, tapi praktiknya, kapitalisme makin mengakar.
Ekonomi kerakyatan yang mestinya mengutamakan UMKM, koperasi, dan peran negara kini tergeser oleh arus liberalisasi. Privatisasi BUMN, penghapusan subsidi, dan kebijakan pro-investor menjadi buktinya. Konsentrasi kekayaan makin ekstrem.
Data Oxfam (2017) menyebut kekayaan empat orang terkaya Indonesia setara dengan 100 juta rakyat termiskin. Tahun 2025, konglomerat makin agresif mencaplok aset triliunan rupiah.
Kapitalisme memang menjanjikan pertumbuhan ekonomi cepat lewat investasi besar. Kendati, distribusi hasilnya minim. Sebaliknya, ekonomi kerakyatan mungkin tak semoncer kapitalisme dalam angka-angka makro, tapi lebih kuat menopang ekonomi rakyat. Dari krisis 1998 hingga pandemi COVID-19, UMKM terbukti tangguh.
Gap data kemiskinan BPS (8,47%) dan Bank Dunia (68,3%) memantulkan paradoks ini: pertumbuhan ekonomi tidak otomatis menciptakan kesejahteraan merata.
Kemiskinan Indonesia adalah persoalan struktural. Oligarki ekonomi-politik menciptakan sistem di mana elite menguasai sumber daya vital, dari tambang hingga media, dan bebas mengatur kebijakan sesuai kepentingannya.
Artinya, 50 orang terkaya Indonesia setara dengan milik 50 juta rakyat terbawah. Ini tentu yang membuat Indonesia masuk empat besar negara dengan ketimpangan terburuk di dunia.
Bantuan sosial pun kerap meleset. Pejabat lokal sibuk memprioritaskan jaringan politik daripada membantu warga miskin. Alih-alih memberdayakan, program bansos justru memperpanjang ketergantungan. Pemerintah terjebak pada politik “bagi-bagi bantuan” tanpa membongkar akar struktural kemiskinan.
Krisis data kemiskinan tersebut kian memprihatinkan. Data BPS yang tampak “baik-baik saja” berisiko membuat anggaran perlindungan sosial jauh di bawah kebutuhan riil.
Imbasnya, program-program seperti PKH dan Sembako hanya menjangkau sebagian kecil masyarakat miskin. Sementara itu, program pemberdayaan UMKM pun mandek lantaran akses modal dan pelatihannya lemah.
Upaya revisi garis kemiskinan oleh BPS dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) pada Juni 2025 adalah langkah awal, tapi tak cukup. Selama DTKS masih amburadul dan data antar kementerian tak terintegrasi, pengentasan kemiskinan hanya jadi angan-angan. Indonesia akan terus gagal memenuhi target SDGs, dan kredibilitas di mata dunia pun dipertaruhkan.
***
*) Oleh : Heru Wahyudi, Dosen di Prodi Administrasi Negara Universitas Pamulang.
*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id
____________
**) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.
| Pewarta | : Hainor Rahman |
| Editor | : Hainorrahman |